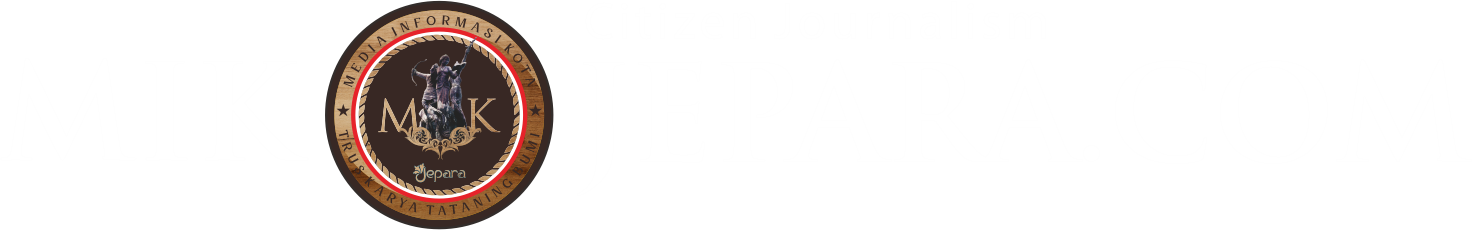MIKJEPARA.com, JEPARA – Ratusan mahasiswa berkumpul dalam diskusi yang digelar Keluarga Mahasiswa Jepara Semarang (KMJS) dan Keluarga Mahasiswa Rembang Semarang (Kamaresa) di Landmark UIN Walisongo, Selasa (23/4/2025).
Sebuah mimbar kecil untuk mengenang RA Kartini sebagai simbol emansipasi wanita ini dinarasikan dengan argumentasi tajam oleh salah satu pembicara, Dr. Muh Khamdan, widyaiswara Kementerian Hukum serta doktor studi perdamaian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pria kelahiran Jepara ini memotret sketsa sosial-budaya Jawa abad ke-18 dan 19 sebagai lanskap sejarah penting kelahiran RA Kartini tahun 1879. Menurutnya, Perang Diponegoro 1825–1830 bukan sekadar perlawanan terhadap kolonialisme, tetapi juga awal dari mutilasi peran perempuan dalam masyarakat Jawa.
Pasca perang, kolonialisme Belanda mengatur ulang sistem sosial. Perempuan yang dulu ikut bergerilya dalam perang, justru “dipingit” atau dijauhkan dari ruang publik dan hak pendidikan.
“Sistem pingitan adalah kolonisasi tubuh perempuan, penjara kultural yang membatasi akses perempuan pada dunia pengetahuan,” ujar Khamdan, mengutip catatan kartinianya. Dalam ruang inilah Kartini tumbuh, memberontak dengan pena dan surat.
RA Kartini, lanjut Khamdan, menulis bukan dari ruang kemewahan, tetapi dari keterpenjaraan. Melalui surat-suratnya kepada sahabat-sahabat Eropa, ia meretas batas-batas feodalisme, patriarki, dan tafsir keagamaan yang mengekang. Tak hanya itu, ia menginspirasi KH Shaleh Darat untuk menulis tafsir Faidhur Rahman, tafsir Qur’an pertama dalam bahasa Jawa aksara pegon.
Diskusi ini menjadi refleksi kontemporer. Yusrul Rizannul Muna dari KMJS menyulut perbincangan dengan nada lirih: “Kita sering memuja Kartini di tataran simbolik, tapi lupa pada perjuangannya yang substansial.” Ia menyoroti paradoks di Jepara hari ini, di mana perempuan lebih tergiur bekerja sebagai buruh pabrik garmen ketimbang melanjutkan pendidikan.
Najih Fawaid dari Kamaresa menambahkan: “Patriarkhi dan kolonialisme sekarang bukan hanya dari luar, tapi menjelma dalam bentuk budaya konsumtif, relasi domestik yang timpang, bahkan algoritma media sosial yang menormalisasi eksploitasi.” Ia setidaknya menyitir surat Kartini kepada Abendanon yang mengkritik dogma yang membungkam nalar dan keberanian perempuan untuk bertanya.
Dr. Khamdan memperluas bahasan ke geopolitik spiritual. “Kartini adalah bagian dari diaspora intelektual Nusantara yang tersambung ke Eropa melalui kakaknya, Sosrokartono, wartawan perang di Eropa.
Ia membaca, merenung, dan melawan melalui surat.” Menurutnya, gagasan Kartini tidak hanya berpengaruh pada pembentukan sekolah perempuan pribumi, tapi juga dalam desain ukir Jepara motif macan kurung, dan awal penataan destinasi wisata bahari Jepara.
Namun semua itu, kata Khamdan, kini tergerus. Di balik gemerlap Kartini Day, Jepara justru mengalami kenaikan angka perceraian yang diajukan oleh istri, meningkatnya penyakit menular seksual, dan kasus pembunuhan bayi. “Ini adalah tragedi modernisasi tanpa kesadaran sejarah,” tegasnya.
Refleksi peserta diskusi pun bergulir lintas bidang. Dari tafsir teologis tentang kebebasan perempuan, hingga kritik terhadap ekonomi politik kawasan industri yang mengekang perempuan dalam kerja upah rendah. Seorang mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin berkomentar, “Kita harus memulai tafsir baru atas Kartini sebagai mujaddid sosial, bukan ikon nasionalisme semu.”
Diskusi juga menyentuh aspek seni dan budaya. Seorang peserta dari Fakultas Dakwah menyinggung bagaimana motif macan kurung bisa dihidupkan kembali sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap sistem sosial yang menjebak perempuan hari ini. Kartini tidak sekadar tokoh, ia adalah konsep perlawanan.
Dalam ruang semi terbuka Landmark UIN Walisongo, diskusi berakhir pukul 18.00 WIB. Tapi perbincangan tak berhenti. Beberapa mahasiswa masih membicarakan tafsir agama yang progresif, bentuk baru gerakan perempuan berbasis komunitas, hingga strategi komunikasi publik untuk mengangkat kembali Kartini sebagai proyek kebudayaan dan peradaban.
Kartini, bagi mereka, bukan sosok yang selesai diperingati setahun sekali. Ia adalah awal dari percakapan panjang antara sejarah dan masa depan, antara kolonialisme dan kebebasan, antara patriarkhi dan keadilan sosial.
Diskusi ini bukan sekadar mengenang, tapi menyusun ulang narasi. Bahwa Kartini tidak mati dalam buku pelajaran. Ia hidup dalam setiap pemikiran kritis, dalam setiap usaha meretas dogma, dalam setiap langkah kecil untuk merebut kembali ruang hidup perempuan yang telah dirampas sejarah dan kapital. Dan di kampus ini, sore itu, Kartini pulang ke rumahnya, ke hati para mahasiswa yang memilih berpikir, menulis, dan bertindak. Sebab revolusi paling sunyi, memang selalu dimulai dari percakapan kecil. (latifa)